Islam adalah agama yang sangat memerhatikan kebersihan dan juga kesehatan. Banyak permasalahan yang memiliki pengaruh bagi kebersihan dan kesehatan tubuh tak luput diajarkan dalam agama ini. Satu diantaranya adalah tentang khitan, yang telah diakui secara medis memiliki manfaat yang besar.
Pembaca yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala, Rasul kita yang mulia –semoga shalawat dan salam tercurah pada beliau- pernah bersabda sebagaimana tersampaikan lewat sahabatnya yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu:
الْفِطْرَةُ خَمْسٌ – أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ – الْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَتَقْلِيْمُ الأََظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ
“Perkara fithrah itu ada lima –atau lima hal berikut ini termasuk dari perkara fithrah yaitu khitan, istihdad (menghilangkan rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan), mencabut bulu ketiak, menggunting kuku, dan memotong kumis. (HR. Bukhari no. 5889, 5891, 6297 dan Muslim no. 597)
Kelima perkara yang disebutkan dalam hadits ini merupakan beberapa perkara kebersihan yang diajarkan oleh Islam.
Pertama: memotong qulfah (kulit penutup) zakar yang bila dibiarkan (tidak dihilangkan) akan menjadi sebab terkumpulnya najis dan kotoran di daerah tersebut hingga menimbulkan berbagai penyakit dan luka.
Kedua: mencukur rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan, baik di daerah qubul ataupun dubur , karena bila dibiarkan rambut tersebut akan bercampur dengan kotoran dan najis (seperti kencing, kotoran, dsb), serta bisa menyebabkan thaharah syar’iyyah (seperti wudhu) tidak bisa sempurna.
Ketiga: menggunting kumis, bila dibiarkan terus tumbuh akan menperjelek wajah. Memanjangkannya juga berarti tasyabbuh (menyerupai) dengan Majusi (para penyembah api).
Keempat: menggunting kuku, bila dibiarkan akan terkumpul kotoran di bawahnya hingga bercampur pada makanan, akibatnya timbullah penyakit. Dan juga bisa menghalangi kesempurnaan thaharah (wudhu) karena kuku yang panjang akan menutup sebagian ujung jari.
Kelima: mencabut bulu ketiak yang bila dibiarkan akan menimbulkan bau yang tak sedap.
Kesimpulannya, menghilangkan perkara-perkara yang disebutkan ini merupakan mahasin (kebagusan/keindahan) Islam, yang Islam datang dengan kebersihan dan kesucian, dengan pengajaran dan pendidikan, agar seorang muslim berada di atas keadaan yang terbaik/terbagus dan bentuk yang paling indah. (Taisirul `Allam, 1/78)
Makna Fithrah
Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaukan dengan fithrah di sini adalah sunnah, demikian dikatakan Al-Imam Al-Khaththabi rahimahullahu dan selainnya. Maknanya, kata mereka, perkara-perkara yang disebutkan dalam hadits di atas termasuk sunnah-sunnah para nabi. Adapula yang berpendapat makna fithrah adalah agama, demikian pendapat yang dipastikan oleh Abu Nu’aim rahimahullahu dalam Al-Mustakhraj.
Abu Syamah rahimahullahu berkata: “Asal makna fithrah adalah penciptaan pada awal permulaannya. Dari makna ini, Allah Subhanahu wa Ta’ala dinyatakan dalam ayat Al-Qur’an sebagai:
فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَاْلأَرْضِ
Maksudnya adalah Dzat yang mengawali penciptaan langit dan bumi (tanpa ada contoh sebelumnya, pent.). Demikian pula dalam sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam:
كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ
Artinya: Setiap anak yang lahir, ia dilahirkan di atas fithrah. Maknanya: si anak dilahirkan di atas perkara yang Allah Subhanahu wa Ta’ala mengawali penciptaan si anak dengannya. Dalam hadits ini ada isyarat kepada firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:
فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
“Fithrah Allah yang Dia menciptakan manusia di atas fithrah tersebut.” (Ar-Rum: 30)
Maknanya: setiap orang seandainya dibiarkan semenjak lahir hingga bisa memandang dengan pikirannya (tanpa dikotori dan dinodai oleh pengaruh-pengaruh dari luar) niscaya akan mengantarkannya ke agama yang benar yaitu tauhid. Yang memperkuat makna ini adalah firman Allah sebelumnya:
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
“Tegakkanlah wajahmu kepada agama Allah yang hanif (lurus, condong kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan). (Demikianlah) fithrah Allah yang Dia menciptakan manusia di atas fithrah tersebut.”
Makna di atas juga diisyaratkan oleh kelanjutan hadits, yaitu:
كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَنَصِّرَانِهِ
“Maka kedua orang tuanya yang menjadikan anak tersebut Yahudi atau Nasrani (memalingkan si anak dari fithrahnya, pent.)”
Dengan demikian yang dimaksudkan dengan fithrah dalam hadits yang menjadi pembahasan kita adalah perkara-perkara yang disebutkan dalam hadits ini yang bila dikerjakan maka pelakunya disifati dengan fithrah yang Allah memfithrahkan para hamba di atasnya, menekankan mereka untuk menunaikannya, dan menyukai untuk mereka agar mereka berada di atas sifat yang paling sempurna dan bentuk/penampilan yang paling tinggi/mulia.”
Al-Qadhi Al-Baidhawi rahimahullahu berkata: “Fithrah ini merupakan sunnah yang terdahulu yang dipilih oleh para nabi dan disepakati oleh syariat. Seakan-akan fithrah ini merupakan perkara yang sudah seharusnya menjadi tabiat/perangai di mana mereka diciptakan di atas tabiat/perangai tersebut.” (Lihat Fathul Bari 10/417, Al-Minhaj 3/139, Tharhut Tatsrib fi Syarhit Taqrib 1/234-235, Nailul Authar 1/161)
Perkara fithrah ini bila dilakukan akan membaguskan penampilan seseorang dan membersihkannya, sebaliknya bila ditinggalkan dan tidak dihilangkan apa yang semestinya dihilangkan akan menjelekkan rupa dan memburukkan penampilan seseorang. Dia akan dianggap kotor dan tercela. (Tharhut Tatsrib fi Syarhit Taqrib 1/235)
Apakah Fithrah Sebatas Lima Perkara Ini?
Perkara fithrah tidak sebatas lima perkara ini, hal ini diketahui dengan lafadz: مِنْ dari kalimat خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ yang menunjukkan tab’idh artinya sebagian, (Ihkamul Ahkam fi Syarhi `Umdatil Ahkam, kitab Ath-Thaharah, bab fil Madzi wa Ghairihi).
Terlebih lagi telah disebutkan dalam hadits-hadits lain, adanya tambahan selain lima perkara tersebut, seperti dalam hadits ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu disebutkan ada 10 hal yang termasuk perkara fithrah yaitu istihdad, mencabut bulu ketiak, menggunting kuku, memotong kumis, memanjangkan jenggot, siwak, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung (istinsyaq), mencuci ruas-ruas jari dan istinja (cebok) . Dengan demikian penyebutan bilangan 5 atau 10 tidak berarti meniadakan tambahan, demikian ucapan mayoritas ulama ushul. (Tharhut Tatsrib fi Syarhit Taqrib 1/236)
Hukum Lima Perkara Fithrah Ini
Ulama berbeda pendapat tentang hukum kelima perkara fithrah yang disebutkan dalam hadits ini, ada yang mengatakan sunnah, adapula yang berpendapat wajib. Namun yang kuat dari pendapat yang ada, wallahu a`lam, lima perkara tersebut ada yang hukumnya wajib dan adapula yang sunnah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu berkata ketika menerangkan hadits Aisyah tentang 10 hal yang termasuk perkara fithrah: “Mayoritas perkara yang disebutkan dalam hadits tentang fithrah tidaklah wajib menurut ulama, sebagiannya diperselisihkan kewajibannya seperti khitan, berkumur-kumur, dan istinsyaq. Dan memang tidak ada penghalang atau tidak ada yang mencegah untuk menggandengkan perkara wajib dengan selain yang wajib sebagaimana penggandengan ini tampak pada firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:
كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
“Makanlah buah-buahan hasil panen kalian apabila telah berbuah dan tunaikanlah haknya (zakatnya) pada hari dipetik hasilnya.” (Al-An`am: 141)
Mengeluarkan zakat tanaman (apabila mencapai nishabnya) hukumnya wajib sementara memakan hasil tanaman itu tidaklah wajib, wallahu a`lam.” (Al-Minhaj, 3/139)
Kita akan sebutkan hukum masing-masing dari lima perkara tersebut dalam perincian pembahasannya berikut ini:
1. KHITAN
Al-Imam Malik, Abu Hanifah, dan sebagian pengikut Al-Imam Asy-Syafi’i berpendapat khitan itu sunnah, tidak wajib. Adapun Al-Imam Asy-Syafi’i, Ahmad dan sebagian Malikiyyah berpendapat hukumnya wajib. Pendapat yang kedua inilah yang rajih/kuat menurut penulis, dengan dasar ketika ada seseorang yang baru masuk Islam, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kepadanya:
أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ
“Buanglah darimu rambut kekufuran dan berkhitanlah.” (HR. Abu Dawud no. 356, dihasankan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu dalam Ash-Shahihah no. 2977 dan Irwaul Ghalil no. 79)
Penulis ‘Aunul Ma’bud (syarah Sunan Abu Dawud) menyatakan perintah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits di atas menunjukkan wajibnya khitan bagi orang yang masuk Islam dan hal itu merupakan tanda keislamannya.
Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu berkata: “Yang rajih/kuat menurut kami, hokum khitan adalah wajib. Demikian madzhab jumhur ulama seperti Malik, Asy-Syafi’i, dan Ahmad. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnul Qayyim. Beliau membawakan 15 sisi pendalilan yang menunjukkan wajibnya khitan. Walaupun satu persatu dari alasan-alasan tersebut tidak dapat mengangkat perkara khitan kepada hukum wajib namun tidak diragukan bahwa pengumpulan alasan-alasan tersebut dapat mengangkatnya. Dikarenakan tidak cukup tempat untuk membawakan semua alasan, maka aku cukupkan dua alasan di antaranya:
Pertama: Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:
ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفاً
“Kemudian Kami wahyukan kepadamu, (Ikutilah millah Ibrahim yang hanif).”
Sementara khitan termasuk millahnya Nabi Ibrahim ‘alaihissalam yang kita diperintahkan untuk mengikutinya, sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu yang disebutkan dalam kitab Ibnul Qayyim rahimahullahu tersebut . Alasan ini merupakan argumen yang paling bagus, sebagaimana dikatakan Al-Baihaqi rahimahullahu yang dinukilkan oleh Al-Hafizh rahimahullahu (10/281).
Kedua: Khitan merupakan syiar Islam yang paling jelas dan paling nampak yang dengannya dibedakan antara seorang muslim dengan seorang Nasrani , sampai-sampai hampir tidak dijumpai ada di kalangan kaum muslimin yang tidak berkhitan. (Tamamul Minnah, hal. 69)
Khitan bagi Wanita
Seperti halnya lelaki, wanita pun disyariatkan berkhitan (Al-Mughni, kitab Ath-Thaharah, fashl Hukmul Khitan) sebagaimana ditunjukkan dalam hadits-hadits berikut ini:
1. Ummu ‘Athiyyah Al-Anshariyyah radhiyallahu ‘anha mengabarkan bahwa di Madinah ada seorang wanita yang biasa mengkhitan, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berpesan kepadanya:
أَشِمِّي وَلاَ تَنْهَكِي، فَإِنَّ ذلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ
“Potonglah tapi jangan dihabiskan (jangan berlebih-lebihan dalam memotong bagian yang dikhitan) karena yang demikian itu lebih terhormat bagi si wanita dan lebih disukai/dicintai oleh suaminya.” (HR. Abu Dawud no. 5271, dishahihkan dalam Shahih Abi Dawud dan Ash-Shahihah no. 721)
2. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
“Apabila bertemu dua khitan , sungguh telah wajib mandi .” (HR. Ahmad 6/239, dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani dalam Ash-Shahihah no. 1261)
3. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda:
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا اْلأَرْبَعِِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
“Apabila seorang laki-laki duduk di antara empat cabang seorang wanita dan khitan yang satu menyentuh khitan yang lain maka sungguh telah wajib mandi.” (HR. Muslim no. 349)
Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu berkata, “Ketahuilah, khitan wanita adalah perkara yang dikenal di kalangan salaf, berbeda halnya dengan apa yang disangka oleh orang yang tidak berilmu. Beberapa atsar berikut ini menunjukkan hal tersebut”.
Kemudian beliau rahimahullahu menyebutkan tiga atsar:
1. Al-Hasan berkata: ‘Utsman bin Abil ‘Ash radhiyallahu ‘anhu diundang untuk menghadiri jamuan makan. Lalu ditanyakan, “Tahukah engkau undangan makan untuk acara apakah ini? Ini acara khitan anak perempuan!” ‘Utsman berkata:
هَذَا شَيْءٌ مَا كُنَّا نَرَاهُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ
“Ini perkara yang tidak pernah kami lihat di masa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.” ‘Utsman pun menolak untuk menyantap hidangan .
2. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad no.1245 (dan didhaifkan oleh Al-Albani dalam Dha’if Adabul Mufrad), Ummul Muhajir berkata, “Aku dan para wanita dari kalangan Romawi menjadi tawanan perang. Maka ‘Utsman menawarkan agar kami mau masuk Islam, namun tidak ada di antara kami yang berislam kecuali aku dan seorang wanita lainnya. ‘Utsman pun memerintahkan, “Khitanilah kedua wanita ini dan sucikanlah keduanya”. Setelah itu jadilah aku berkhidmat kepada ‘Utsman.
3. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad no.1247 (dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Shahih Adabul Mufrad), Ummu ‘Alqamah mengabarkan:
أَنَّ بَنَاتَ أَخِي عَائِشَةَ خُتِنَّ فَقِيْلَ لِعَائِشَةَ: أَلاَ نَدْعُو لَهُنَّ مَنْ يُلْهِيْهِنَّ؟ قَالَتْ: بَلَى. فَأَرْسَلْتُ إِلَى عُدَيِّ فَأَتَاهُنَّ فَمَرَّتْ عَائِشَةُ فِي الْبَيْتِ فَرَأَتْهُ يَتَغَنَّى وَيُحَرِّكُ رَأْسَهُ طَرَبًا – وَكَانَ ذَا شَعْرٍ كَثِيْرٍ – فَقَالَتْ: أُفٍّ، شَيْطَانٌ أَخْرِجُوْهُ، أَخْرِجُوْهُ
“Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ‘Aisyah dikhitan, maka ditanyakan kepada ‘Aisyah, “Bolehkah kami memanggil seseorang yang dapat menghibur mereka?” ‘Aisyah mengatakan, “Ya, boleh.” Maka aku mengutus seseorang untuk memanggil ‘Uday, lalu dia pun mendatangi anakanak perempuan itu. Kemudian lewatlah ‘Aisyah di rumah itu dan melihatnya sedang bernyanyi sambil menggerak-gerakkan kepalanya, sementara dia mempunyai rambut yang lebat. ‘Aisyah pun berkata, “Hei, setan! Keluarkan dia, keluarkan dia!” (Lihat Ash-Shahihah, 2/348-349)
Yang perlu jadi perhatian, ada perbedaan hukum khitan lelaki dengan hokum khitan bagi wanita, walaupun ada pendapat di kalangan ulama yang menyamakan (sama-sama wajib). Tampak perbedaan hukum tersebut dalam hadits Syaddad bin Aus radhiyallahu ‘anhu berikut ini:
الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ
“Khitan itu sunnah bagi lelaki dan pemuliaan bagi wanita.”
Namun kata Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu hadits ini tidak tsabit, karena datang dari riwayat Hajjaj bin Arthah, sementara ia tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, dikeluarkan hadits ini oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Baihaqi . Namun ada syahid (pendukung) dari hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Musnad Asy-Syamiyyin, dari jalan Sa’id bin Bisyr dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, namun Sa’id ini diperselisihkan. Abusy Syaikh dan Al-Baihaqi mengeluarkannya dari sisi lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma. Al-Baihaqi juga mengeluarkannya dari hadits Abu Ayyub radhiyallahu ‘anhu. (Fathul Bari, 10/419)
Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin rahimahullahu menyatakan telah terjadi perselisihan pendapat dalam hukum khitan, dan pendapat yang paling dekat dengan kebenaran menyatakan bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi wanita. Perbedaan hukum khitan antara laki-laki dan perempuan itu dikarenakan khitan pada laki-laki mengandung maslahat yang berkaitan dengan syarat shalat dan termasuk perkara thaharah (bersuci). Apabila kulup (kulit yang menutupi ujung zakar) tidak dihilangkan, maka air kencing yang keluar tertahan dan terkumpul di kulup tersebut hingga berakibat peradangan pada bagian tersebut, ataupun keluar tanpa sengaja bila zakar itu bergerak, sehingga menajisi. Adapun pada wanita, tujuan khitan adalah meredakan syahwatnya, bukan untuk menghilangkan kotoran. (Majmu’ Fatawa wa Rasa`il Fadhilatusy Syaikh Muhammad ibnu Shalih Al-’Utsaimin 11/117, Asy-Syarhul Mumti’, 1/110)
Dengan demikian khitan hanya wajib bagi laki-laki, tidak wajib bagi wanita. Pendapat ini juga yang dipilih oleh Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi (Asy-Syarhul Mumti’, 1/109)
Hukum Orang yang Tidak Mau Dikhitan
Al-Haitami berkata: “Yang benar jika diwajibkan bagi kita khitan, lalu ditinggalkan tanpa udzur maka pelakunya fasik. Namun pahamilah bahwasanya pembicaraan di sini hanya ditujukan pada anak laki-laki tanpa menyertakan anak perempuan. Laki-laki difasikkan bila meninggalkan khitan tanpa udzur dan lazim dari sebutan fasik tersebut bahwa perbuatan itu termasuk dosa besar.” (Az-Zawajir 2/162)
Bagian yang Dikhitan
Khitan pada anak laki-laki dilakukan dengan cara memotong kulup (qulfah) atau kulit yang menutupi ujung zakar. Minimal menghilangkan apa yang menutupi ujung zakar dan disenangi untuk mengambil seluruh kulit di ujung zakar tersebut. Sedangkan pada wanita, dilakukan dengan memotong kulit di bagian paling atas kemaluan di atas vagina yang berbentuk seperti biji atau jengger ayam jantan . Yang harus dilakukan pada khitan wanita adalah memotong ujung kulit dan bukan memotong habis bagian tersebut. (Al-Majmu Syarhul Muhadzdzab 1/349, Fathul Bari 10/420, Nailul Authar 1/162, 165)
Ibnu Taimiyyah rahimahullahu ketika ditanya mengenai khitan wanita, beliau memberikan jawaban bahwa wanita dikhitan dengan memotong kulit yang paling atas yang berbentuk seperti jengger ayam jantan . (Majmu’ Fatawa, 21/114)
Faidah
Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin rahimahullahu mengatakan, pelaksanaan khitan itu seharusnya dilakukan oleh seorang dokter yang ahli (atau tenaga kesehatan lainnya, pent.) yang mengetahui bagaimana cara mengkhitan. Bila seseorang tidak mendapatkannya maka ia bisa mengkhitan dirinya sendiri jika memang mampu melakukannya dengan baik. Nabi Ibrahim ‘alaihissalam mengkhitan dirinya sendiri. Orang yang mengkhitan boleh melihat aurat yang dikhitan walaupun usia yang dikhitan telah mencapai sepuluh tahun, kebolehan ini dikarenakan adanya kebutuhan. (Asy-Syarhul Mumti`, 1/110)
Waktu Khitan
Ada perbedaan pendapat tentang kapan waktu disyariatkannya khitan. Jumhur ulama berpendapat tidak ada waktu khusus untuk melaksanakan khitan. (Nailul Authar, 1/165)
Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu menjelaskan, untuk melaksanakan khitan ada dua waktu, waktu yang wajib dan waktu yang mustahab (sunnah). Waktu yang wajib adalah ketika seorang anak mencapai baligh , sedangkan waktu yang sunnah adalah sebelum baligh. Boleh pula melakukannya pada hari ketujuh setelah kelahiran. Juga disunnahkan untuk tidak mengakhirkan pelaksanaan khitan dari waktu yang sunnah kecuali karena ada uzur. (dinukil dari Fathul Bari, 10/421)
Ibnul Mundzir rahimahullahu mengatakan, “Tidak ada larangan yang ditetapkan oleh syariat yang berkenaan dengan waktu pelaksanaan khitan ini, juga tidak ada batasan waktu yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan khitan tersebut, begitu pula sunnah yang harus diikuti. Seluruh waktu diperbolehkan. Tidak boleh melarang sesuatu kecuali dengan hujjah dan kami juga tidak mengetahui adanya hujjah bagi orang yang melarang khitan anak kecil pada hari ketujuh.” (dinukil dari Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab, 1/352)
Namun Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu menyebutkan dua hadits yang menunjukkan adanya pembatasan waktu khitan:
Pertama: Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu 'anhuma, ia menyatakan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengaqiqahi cucu beliau Al-Hasan dan Al-Husain, dan mengkhitan keduanya pada hari ketujuh.
Kedua: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, “Ada tujuh perkara yang sunnah dilakukan pada hari ketujuh seorang bayi, yaitu diberi nama, dikhitan…”
Kemudian beliau menyatakan bahwa walaupun kedua hadits di atas memiliki kelemahan , namun kedua hadits ini saling menguatkan karena makhraj kedua hadits ini berbeda dan tidak ada dalam sanadnya rawi yang tertuduh berdusta. Kalangan Syafi’iyyah mengambil hadits ini, sehingga mereka menganggap sunnah dilakukan khitan pada hari ketujuh dari kelahiran seorang anak, sebagaimana disebutkan dalam Al-Majmu’ (1/307) dan selainnya. Batas tertinggi dilakukannya khitan adalah sebelum seorang anak baligh. Ibnul Qayyim rahimahullahu berkata: “Tidak boleh bagi si wali menunda dilakukannya khitan anak (yang dibawah perwaliannya) sampai si anak melewati masa baligh.” (Tamamul Minnah, hal. 68)
Lebih afdhal/utama bila khitan ini dilakukan ketika anak masih kecil, karena lebih cepat sembuhnya dan agar si anak tumbuh di atas keadaan yang paling sempurna. (Ar-Raudhul Murbi’ Syarh Zadil Mustaqni’ 1/35, Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi, Asy-Syaikh Shalih Fauzan 1/34)2. ISTIHDAD
2. ISTIHDAD
Istihdad adalah mencukur rambut kemaluan. Perbuatan ini diistilahkan istihdad karena mencukurnya dengan menggunakan hadid yaitu pisau cukur. (Ihkamul Ahkam fi Syarhi ‘Umdatil Ahkam, kitab Ath-Thaharah, bab fil Madzi wa Ghairihi)
Dalam hadits Ibnu ‘Umar radhiyallahu 'anhuma yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, hadits ‘Aisyah dan hadits Anas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, istihdad ini disebutkan dengan lafadz: حَلْقُ الْعَانَةِ (mencukur ‘anah). Pengertian ‘anah adalah rambut yang tumbuh di atas kemaluan dan sekitarnya.
Istihdad hukumnya sunnah. Tujuannya adalah untuk kebersihan. Dan istihdad ini juga disyariatkan bagi wanita, sebagaimana ditunjukkan dalam hadits:
أَمْهِلُوْا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلاً – أَيْ عِشَاءً – لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ
“Pelan-pelanlah, jangan tergesa-gesa (untuk masuk ke rumah kalian) hingga kalian masuk di waktu malam –yakni waktu Isya'– agar para istri yang ditinggalkan sempat menyisir rambutnya yang acak-acakan/kusut dan sempat beristihdad (mencukur rambut kemaluan).” (HR. Al-Bukhari no. 5245 dan Muslim)
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepada Jabir bin Abdillah radhiyallahu 'anhuma:
إِذَا دَخَلْتَ لَيْلاً فَلاَ تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ وتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ
“Apabila engkau telah masuk ke negerimu (sepulang dari bepergian/safar) maka janganlah engkau masuk menemui istrimu hingga ia sempat beristihdad dan menyisir rambutnya yang acak-acakan/kusut.” (HR. Al-Bukhari no. 5246)
Yang utama rambut kemaluan tersebut dicukur sampai habis tanpa menyisakannya. Dan dibolehkan mengguntingnya dengan alat gunting, dicabut, atau bisa juga dihilangkan dengan obat perontok rambut, karena yang menjadi tujuan adalah diperolehnya kebersihan. (Tharhut Tatsrib fi Syarhit Taqrib 1/239, Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab 1/342, Al-Mughni, kitab Ath-Thaharah, fashl Hukmul Istihdad)
Al-Imam Ahmad rahimahullahu ketika ditanya tentang boleh tidaknya menggunakan gunting untuk menghilangkan rambut kemaluan, beliau menjawab, “Aku berharap hal itu dibolehkan.” Namun ketika ditanya apakah boleh mencabutnya, beliau balik bertanya, “Apakah ada orang yang kuat menanggung sakitnya?”
Abu Bakar ibnul ‘Arabi rahimahullahu berkata, “Rambut kemaluan ini merupakan rambut yang lebih utama untuk dihilangkan karena tebal, banyak dan kotoran bisa melekat padanya. Beda halnya dengan rambut ketiak.”
Waktu yang disenangi untuk melakukan istihdad adalah sesuai kebutuhan dengan melihat panjang pendeknya rambut yang ada di kemaluan tersebut. Kalau sudah panjang tentunya harus segera dipotong/dicukur. (Al-Minhaj 3/140, Fathul Bari 10/422, Al-Mughni, kitab Ath-Thaharah, fashl Hukmul Istihdad)
Pendapat yang masyhur dari jumhur ulama menyatakan yang dicukur adalah rambut yang tumbuh di sekitar zakar laki-laki dan kemaluan wanita. (Tharhut Tatsrib fi Syarhit Taqrib 1/239)
Adapun rambut yang tumbuh di sekitar dubur, terjadi perselisihan pendapat tentang boleh tidaknya mencukurnya. Ibnul ‘Arabi rahimahullahu mengatakan bahwa tidak disyariatkan mencukurnya, demikian pula yang dikatakan Al-Fakihi dalam Syarhul ‘Umdah. Namun tidak ada dalil yang menjadi sandaran bagi mereka yang melarang mencukur rambut yang tumbuh di dubur ini. Adapun Abu Syamah berpendapat, “Disunnahkan menghilangkan rambut dari qubul dan dubur. Bahkan menghilangkan rambut dari dubur lebih utama karena dikhawatirkan di rambut tersebut ada sesuatu dari kotoran yang menempel, sehingga tidak dapat dihilangkan oleh orang yang beristinja (cebok) kecuali dengan air dan tidak dapat dihilangkan dengan istijmar (bersuci dari najis dengan menggunakan batu).” Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu menguatkan pendapat Abu Syamah ini. (Fathul Bari, 10/422)
Mencukur rambut kemaluan ini tidak boleh bahkan haram dilakukan oleh orang lain, terkecuali orang yang dibolehkan menyentuh dan memandang kemaluannya seperti suami dan istri. (Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab 1/342, Fathul Bari 10/423)
3. MENCABUT RAMBUT KETIAK
Mencabut rambut ketiak disepakati hukumnya sunnah dan disenangi memulainya dari ketiak yang kanan, dan bisa dilakukan sendiri atau meminta kepada orang lain untuk melakukannya. Afdhal-nya rambut ini dicabut, tentunya bagi yang kuat menanggung rasa sakit. Namun bila terpaksa mencukurnya atau menghilangkannya dengan obat perontok maka tujuannya sudah terpenuhi. Ibnu Abi Hatim dalam bukunya Manaqib Asy-Syafi’i meriwayatkan dari Yunus bin ‘Abdil A’la, ia berkata, “Aku masuk menemui Al-Imam Asy-Syafi’i rahimahullahu dan ketika itu ada seseorang yang sedang mencukur rambut ketiaknya. Beliau berkata, ‘Aku tahu bahwa yang sunnah adalah mencabutnya, akan tetapi aku tidak kuat menanggung rasa sakitnya’.” (Al-Minhaj 3/140, Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab 1/341, Fathul Bari 10/423, Tharhut Tatsrib fi Syarhit Taqrib 1/244)
Harb berkata, “Aku katakan kepada Ishaq: ‘Mencabut rambut ketiak lebih engkau sukai ataukah menghilangkannya dengan obat perontok?’ Ishaq menjawab, ‘Mencabutnya, bila memang seseorang mampu’.” (Al-Mughni, kitab Ath-Thaharah, fashl Hukmu Natful Ibthi)
4. MEMOTONG KUKU
Hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan yang dihilangkan adalah kuku yang tumbuh melebihi ujung jari, karena kotoran dapat tersimpan/tersembunyi di bawahnya dan juga dapat menghalangi sampainya air wudhu. Disenangi untuk melakukannya dari kuku jari jemari kedua tangan, baru kemudian kuku pada jari-jemari kedua kaki. Tidak ada dalil yang shahih yang dapat menjadi sandaran dalam penetapan kuku jari mana yang terlebih dahulu dipotong. Ibnu Daqiqil Ied rahimahullahu berkata, “Orang yang mengatakan sunnahnya mendahulukan jari tangan daripada jari kaki ketika memotong kuku perlu mendatangkan dalil, karena kemutlakan dalil anjuran memotong (tanpa ada perincian mana yang didahulukan) menolak hal tersebut.” Namun mendahulukan bagian yang kanan dari jemari tangan dan kaki ada asalnya, yaitu hadits ‘Aisyah radhiyallahu 'anha yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyenangi memulai dari bagian kanan. (Lihat Fathul Bari 10/425, Tharhut Tatsrib fi Syarhit Taqrib 1/241, Al-Mughni, kitab Ath-Thaharah, fashl Hukmu Taqlimul Azhfar)
Tidak ada dalil yang shahih tentang penentuan hari tertentu untuk memotong kuku, seperti hadits:
كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَشَارِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyenangi memotong kuku dan kumisnya pada hari Jum’at.”
Hadits ini merupakan salah satu riwayat mursal dari Abu Ja’far Al-Baqir, sementara hadits mursal termasuk hadits dhaif. Wallahu a’lamu bish-shawab.
Dengan demikian memotong kuku dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan. Al-Hafizh rahimahullahu menyatakan melakukannya pada setiap hari Jum’at tidaklah terlarang, karena bersungguh-sungguh membersihkan diri pada hari tersebut merupakan perkara yang disyariatkan. (Fathul Bari, 10/425)
Akan tetapi kuku-kuku tersebut jangan dibiarkan tumbuh lebih dari 40 hari karena hal itu dilarang, sebagaimana dalam hadits Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, dia berkata:
وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمِ اْلأَظْفَارِ وَنَتْفِ اْلإِبْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لاَ نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً
“Ditetapkan waktu bagi kami dalam memotong kumis, menggunting kuku, mencabut rambut ketiak dan mencukur rambut kemaluan, agar kami tidak membiarkannya lebih dari empat puluh malam.” (HR. Muslim no. 598)
Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu berkata: “Pendapat yang terpilih adalah ditetapkan waktu 40 hari sebagaimana waktu yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, sehingga tidak boleh dilampaui. Dan tidaklah teranggap menyelisihi sunnah bagi orang yang membiarkan kuku/rambut ketiak dan kemaluannya panjang (tidak dipotong/dicukur) sampai akhir dari waktu yang ditetapkan.” (Nailul Authar, 1/163)
Adapun Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu mengatakan, “Makna hadits di atas adalah tidak boleh meninggalkan perbuatan yang disebutkan melebihi 40 hari. Bukan maksudnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menetapkan waktu untuk mereka agar membiarkan kuku, rambut ketiak dan rambut kemaluan tumbuh selama 40 hari.” (Al-Minhaj 3/140, Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab 1/340)
Dalam memotong kuku boleh meminta orang lain untuk melakukannya, karena hal ini tidaklah melanggar kehormatan diri. Terlebih lagi bila seseorang tidak bisa memotong kuku kanannya dengan baik karena kebanyakan orang tidak dapat menggunakan tangan kirinya dengan baik untuk memotong kuku, sehingga lebih utama baginya meminta orang lain melakukannya agar tidak melukai dan menyakiti tangannya. (Tharhut Tatsrib fi Syarhit Taqrib, 1/243)
Faidah
Apakah bekas potongan kuku itu dibuang begitu saja atau dipendam?
Al-Hafizh rahimahullahu menyatakan bahwa Al-Imam Ahmad rahimahullahu pernah ditanya tentang hal ini, “Seseorang memotong rambut dan kuku-kukunya, apakah rambut dan kuku-kuku tersebut dipendam atau dibuang begitu saja?” Beliau menjawab, “Dipendam.” Ditanyakan lagi, “Apakah sampai kepadamu dalil tentang hal ini?” Al-Imam Ahmad rahimahullahu menjawab, “Ibnu ‘Umar memendamnya.”
Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari hadits Wa`il bin Hujr disebutkan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk memendam rambut dan kuku-kuku. Alasannya, kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu, “Agar tidak menjadi permainan tukang sihir dari kalangan anak Adam (dijadikan sarana untuk menyihir, pent.).” Al-Hafizh rahimahullahu juga berkata, “Orang-orang yang berada dalam madzhab kami (madzhab Asy-Syafi'i, pent.) menyenangi memendam rambut dan kuku (karena rontok atau sengaja dipotong, pent.) karena rambut dan kuku tersebut merupakan bagian dari manusia. Wallahu a’lam.” (Fathul Bari, 10/425)
5. MEMOTONG KUMIS
Kumis adalah rambut yang tumbuh di atas bibir bagian atas. Telah datang perintah dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk memotong kumis dan tidak membiarkannya terus tumbuh hingga menutupi kedua bibir. Ibnu ‘Umar radhiyallahu 'anhuma menyampaikan dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:
أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى
“Potonglah kumis dan biarkanlah jenggot (sebagaimana adanya tanpa dikurangi dan dipotong).” (HR. Muslim no. 599)
Memotong kumis dan memanjangkan jenggot –atau membiarkannya tumbuh apa adanya– merupakan amalan yang dilakukan untuk menyelisihi orang-orang musyrikin dan Majusi (para penyembah api). Karena kebiasaan mereka adalah membiarkan kumis tumbuh hingga menutupi bibir, sementara jenggot mereka cukur. Perintah menyelisihi mereka ini dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:
خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ، أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى
“Selisihilah orang-orang musyrikin, potonglah kumis dan biarkanlah jenggot (sebagaimana adanya tanpa dikurangi dan dipotong).” (HR. Muslim no. 600)
Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
جُزُّو الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوْسَ
“Potonglah kumis dan biarkanlah jenggot (sebagaimana adanya tanpa dikurangi dan dipotong), selisihilah orang-orang Majusi.” (HR. Muslim no. 602)
Dengan demikian dalam masalah memotong kumis dan memanjangkan jenggot ini, ada dua tujuan:
1. Menyelisihi kebiasaan orang ‘ajam (non Arab), dalam hal ini orang-orang Majusi/Persia ataupun musyrikin.
2. Menjaga kebersihan daerah bibir dan sekitarnya yang merupakan tempat masuknya makanan dan minuman. Al-Imam Ath-Thahawi rahimahullahu menyatakan “Memotong kumis dilakukan dengan mengambil/memotong kumis yang panjangnya melebihi bibir, sehingga tidak mengganggu ketika makan dan tidak terkumpul kotoran di dalamnya.”
Batasan kumis yang dipotong adalah dipotong sampai tampak ujung bibir, bukan menipiskan dari akarnya. Sementara hadits yang menyebutkan: أَحْفُوا الشَّوَارِبَ (“Potonglah kumis…”) yang dimaukan adalah memotong bagian kumis yang panjang hingga tidak menutupi kedua bibir.
Memang dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Mayoritas ulama Salaf berpendapat kumis itu dicukur sampai habis sama sekali, berdalil dengan dzahir hadits Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:
أَحْفُوا وَانْهَكُوا
“Potonglah kumis dan habiskanlah.” (HR. Al-Bukhari no. 5893)
Ini merupakan pendapat orang-orang Kufah.
Namun kebanyakan mereka berpendapat dilarang mencukur kumis dan menghabiskannya sama sekali, demikian pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini dipegangi Al-Imam Malik rahimahullahu. Bahkan beliau memandang mencukur kumis sampai habis adalah perbuatan mencincang dan beliau memerintahkan agar pelakunya diberi ganjaran sebagai pelajaran. Dengan demikian, menurut pendapat yang kedua ini kumis tidak dihabiskan sama sekali tapi diambil/dipotong sesuai dengan kadarnya yang dengannya akan tampak ujung bibir (tidak tertutup kumis).
Sebagian ulama, seperti Ath-Thabari, punya pendapat lain. Beliau menganggap kedua-duanya boleh, sehingga seseorang boleh memilih apakah ia ingin mencukur habis kumisnya atau membiarkannya namun tidak sampai menutupi bibir (dipotong bagian yang berlebihan). Beliau berkata, “As-Sunnah menunjukkan bahwa kedua perkara tersebut dibolehkan dan tidak saling bertentangan. Karena lafadz القَصُّ1 menunjukkan mengambil sebagian, sedangkan lafadz اْلإِحْفَاء2 menunjukkan mengambil seluruhnya. Berarti keduanya tsabit (ada perintah/tuntunannya) sehingga seseorang diberi pilihan untuk melakukan apa yang diinginkannya.”
Ibnu ‘Abdil Bar rahimahullahu berkata, “اْلإِخْفَاءُ bisa dimungkinkan maknanya mengambil keseluruhan. Namun القَصُّ mufassar yakni menerangkan/menjelaskan apa yang dimaukan. Dan apa yang menerangkan/menjelaskan lebih dikedepankan dari yang global.”3
Hukum Memanjangkan Jenggot
Hukum memanjangkan jenggot adalah wajib dan haram mencukurnya sebagaimana dipahami dari dalil yang banyak. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu menerangkan sisi pendalilan wajibnya memanjangkan jenggot ini, antara lain:
1. Adanya perintah dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk memanjangkannya dan membiarkannya apa adanya. Sementara hukum asal dari perintah beliau adalah wajib, berdasarkan ayat:
فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ
“Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah beliau dari tertimpa fitnah atau mereka ditimpa azab yang pedih.” (An-Nur: 63)
2. Haramnya laki-laki menyerupai (tasyabbuh) dengan wanita, sebagaimana tersebut dalam hadits:
لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمتُشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ
“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan melaknat wanita yang menyerupai laki-laki.” (HR. Al-Bukhari no. 5885, 6834)
Sementara, bila seorang lelaki mencukur jenggotnya berarti ia menyerupai wanita dalam penampilan dzahirnya. Dengan begitu, berarti haram mencukur jenggot dan wajib memeliharanya.
3. Allah Subhanahu wa Ta’ala melaknat an-namishat yaitu wanita yang mencabut/mencukur rambut alisnya dengan tujuan untuk berhias, seperti dalam hadits dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu 'anhu secara marfu’:
لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ
“Allah melaknat wanita yang mentato dan minta ditato, wanita yang mencabut rambut alisnya dan wanita yang minta dicabut, wanita yang mengikir giginya untuk keindahan, yang mengubah ciptaan Allah.” (HR. Al-Bukhari no. 5939 dan Muslim no. 2125)
Sementara orang yang mencukur jenggotnya bertujuan ingin tampil bagus menurut anggapannya. Padahal dengan berbuat demikian, ia telah mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia termasuk dalam hukum an-namishat, tidak ada bedanya, kecuali hanya dalam lafadz/sebutan.
4. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjadikan memanjangkan jenggot ini termasuk perkara fithrah sebagaimana menggunting kuku, mencukur rambut kemaluan, dan selainnya. (Tamamul Minnah hal. 82)
Perintah memanjangkan jenggot ini tentunya dikhususkan bagi lelaki, karena bila ada seorang wanita tumbuh rambut pada dagunya maka disenangi baginya untuk mencukurnya, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu. (Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab 1/343, Fathul Bari, 10/431)
Sebagaimana dinyatakan dalam edisi terdahulu bahwa sunnah-sunnah fithrah tidak sebatas lima perkara yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu. Karena dalam hadits lain seperti dalam hadits ‘Aisyah radhiyallahu 'anha disebutkan sunnah-sunnah fithrah yang lain selain lima perkara yang telah dijelaskan di atas. Ummul Mukminin ‘Aisyah radhiyallahu 'anha berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ اْلأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ اْلإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ. قَالَ زَكَرِيَّاءُ: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ، إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةُ.
“Sepuluh perkara berikut ini termasuk perkara fithrah yaitu memotong kumis, memanjang jenggot, siwak, istinsyaq, memotong kuku, mencuci ruas-ruas jari, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan dan istinja.” Zakariyya berkata: “Mush’ab berkata, ‘Aku lupa yang kesepuluh, kecuali kalau dimasukkan madhmadhah (berkumur-kumur)’.” (HR. Muslim no. 603)
Demikian tuntunan yang indah dari agama ini. Namun kebanyakan orang tidak mengetahui serta tidak mengamalkannya. Bahkan mereka melakukan yang sebaliknya karena taqlid buta kepada orang-orang kafir.
Dengan begitu apa yang dilakukan oleh anak-anak muda sekarang ini dengan memanjangkan kuku dan apa yang dilakukan oleh kaum lelaki dengan memanjangkan kumis merupakan perkara yang dilarang secara syariat dan dianggap buruk/jelek oleh akal dan perasaan. Sungguh agama Islam ini tidaklah memerintahkan kecuali kepada segala yang sifatnya indah, dan Islam tidaklah melarang kecuali dari perbuatan yang jelek/buruk. Namun taqlid buta kepada Barat telah membalikkan hakikat, sehingga yang jelek dianggap bagus sementara yang bagus menurut perasaan, akal, dan syariat justru dijauhi. (Taisirul ‘Allam, 1/79)
Wallahu ta’ala a’lam bish-shawab.
1 Sebagaimana disebutkan dalam hadits:
الْفِطْرَةُ خَمْسٌ –أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ– الْخِتَانُ وَاْلاِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ اْلإِبْطِ وَتَقْلِيْمُ اْلأََظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ
2 Sebagaimana disebutkan dalam hadits:
أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى
3 Tharhut Tatsrib fi Syarhit Taqrib (1/240), Al-Minhaj (3/ 140 dan 144), Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab (1/340), Ihkamul Ahkam fi Syarhi ‘Umdatil Ahkam, kitab Ath-Thaharah, bab fil Madzi wa Ghairihi, Fathul Bari (10/426), Nailul Authar (1/163).
sumber: http://pentasatriya.multiply.com


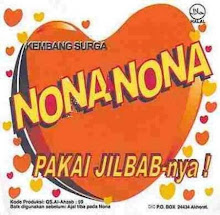
Tidak ada komentar:
Posting Komentar